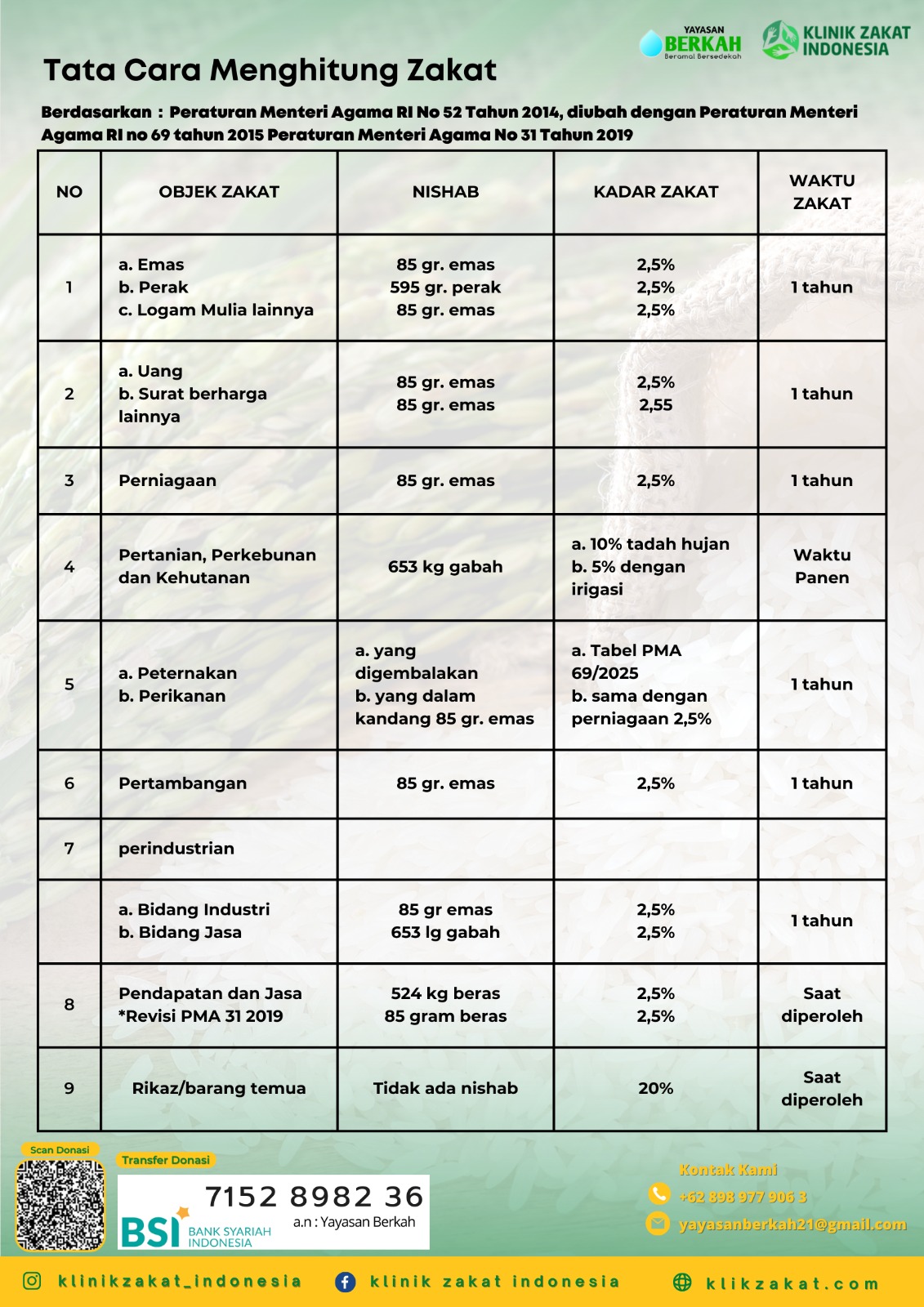Oleh :
Raihan Ariatama
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2023
MENJELANG kontestasi elektoral Pemilu 2024, ketegangan antarwarga negara akan mengalami peningkatan. Sebabnya adalah perbedaan pandangan dan pilihan politik yang terfasilitasi melalui rangkaian tahapan pemilu.
Karenanya, ketegangan antarwarga negara tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menjelma konflik, kerusuhan, dan kekerasan.
Dalam demokrasi, ketegangan antarwarga negara akibat perbedaan pilihan politik merupakan kondisi yang biasa. Jika tidak ada ketegangan, kita patut curiga dengan kondisi demokrasi kita; apakah rakyat sudah takut untuk mengungkapkan perbedaan pilihan politiknya ataukah rakyat telah letih untuk berpartisipasi dalam politik karena ujungnya sama saja–tidak ada perubahan dalam kehidupan publik.
Persoalannya bukan terletak dalam ketegangan antarwarga tersebut, melainkan pada polarisasi politik yang terbentuk akibat ketegangan tersebut, yang menyebabkan masyarakat terbelah.
Apalagi, ketegangan tersebut dipicu oleh politisasi identitas yang berlebihan, yang dibalut dengan sentimen rasial, etnisitas dan agama. Sehingga, dampaknya adalah jurang keterbelahan masyarakat yang semakin melebar dan mendalam, sekaligus membekas dalam memori kolektif masyarakat.
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi titik awal polarisasi politik, menguat pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 dan semakin tidak terkendali dalam Pilpres 2019. Residu-residu polarisasi politik sampai saat ini masih membekas.
Cebong dan kampret serta kadrun–identitas-identitas kelompok yang diasosiasikan dengan afiliasi keagamaan dalam konteks politik–masih mewarnai diskursus dan perilaku politik kita hingga hari ini. Prediksinya, polarisasi politik akan menentukan pilihan pemilih dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.
Politik Identitas dan Masyarakat yang Terbelah
Apakah politik identitas berbanding lurus dengan polarisasi politik dan keterbelahan masyarakat? Menurut Rumadi Ahmad (2022), tidak semua politik identitas memiliki daya rusak terhadap keutuhan bangsa. Dengan kata lain, politik identitas tidak berarti menimbulkan polarisasi politik dan keterbelahan masyarakat.
Dalam babakan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, politik identitas meresonansikan nada persatuan untuk melawan kolonialisme. Kita melihat bagaimana politik identitas berlandaskan pada nasionalisme dan agama memainkan peran yang sangat penting dalam merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
Bahkan, perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan serta merawat keutuhan bangsa dalam napas kebinekaan Indonesia diperkuat dengan dalil-dalil agama sehingga menjaga Indonesia bukan sekadar keharusan politik sebagai sebuah bangsa, melainkan kewajiban agama yang di dalamnya mengandung nilai-nilai eskatologis.
Karena alasan tersebut, maka biang masalahnya bukan pada politik identitas. Lalu di mana letak permasalahannya? Menurut Rumadi Ahmad (2022), hanya politik identitas dengan kebencian terhadap kelompok yang lain, yang dapat membawa demokrasi Indonesia ke dalam kubangan polarisasi politik dan keterbelahan masyarakat yang tidak berkesudahan. Kita perlu menggarisbawahi predikat “kebencian” tersebut.
Politik identitas dengan kebencian digaungkan dengan narasi konflik biner, antara kita versus mereka, yang menurut Eve Warbuton (2021) memperlakukan lawan politik sebagai musuh, “pihak luar” yang tidak diakui, sekaligus menjadi ancaman eksistensial. Akibatnya, pemilu menjadi arena pertarungan politik untuk saling melenyapkan lawan politik, bukan sekadar saling menegasikan lawan politik.
Politik identitas dengan kebencian tersebut menjadi momok yang menakutkan, yang menyebabkan keterbelahan masyarakat, sekaligus mengancam keutuhan dan kebinekaan bangsa ini. Apalagi, narasi kebencian tersebut diamplifikasi melalui ruang publik baru yang tingkat penyebarannya sangatlah cepat, yakni platform media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya.
Di media sosial, kendalinya terletak pada masing-masing individu pengguna sehingga narasi-narasi yang berkembang di dalamnya tidak melalui kurasi dan penyuntingan terlebih dahulu, sebagaimana lumrah dilakukan di media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya.
Satu-satunya kurasi di media sosial adalah kurasi algoritma, yang mengurung pengguna media sosial ke dalam echo chamber (ruang gema), di mana seseorang “dipaksa” untuk hanya mengonsumsi informasi yang searah yang sesuai dengan pendapat dan keyakinannya. Dalam arti lain, kurasi algoritma media sosial membuat seseorang–meskipun tampak berdiskusi dengan orang lain–bercakap-cakap dengan pikiran dan keyakinannya atau pandangan orang lain yang serupa dengan pikiran dan keyakinannya.
Sehingga, yang terjadi sebenarnya di media sosial adalah monolog, bukan dialog. Akibatnya, menurut Agus Sudibyo (2022), dengan karakter media sosial yang demikian, sangat sulit menjembatani segregasi antarkelompok, bahkan justru memperdalam segregasi tersebut.
Kondisi ini ditunjang oleh era yang saat ini kita alami, era pascakebenaran (post-truth), suatu era ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh membentuk opini publik ketimbang fakta-fakta objektif. Politik identitas dengan kebencian mempertebal emosi dan keyakinan pribadi tersebut; suatu perpaduan yang saling melengkapi.
Fakta-fakta objektif akan diabaikan, bahkan harus diubah, apabila bertentangan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Dengan kata lain, di era pascakebenaran, fakta objektif akan diterima sebagai fakta objektif apabila mengonfirmasi emosi dan keyakinan pribadi.
Dengan karakteristik media sosial dan kondisi era pascakebenaran tersebut, politik identitas dengan kebencian dapat tumbuh sumbur, yang pada gilirannya akan mempertajam pembelahan politik masyarakat.
Kita tidak menginginkan politik Indonesia dibangun di atas fondasi politik balas dendam. Karenanya, keterbelahan masyarakat yang dipicu oleh politik identitas dengan kebencian tersebut tidak boleh dibiarkan.
Selain berimplikasi pada retaknya kebinekaan Indonesia, menurut Thomas Carothers dan Andrew O’Donuhue (2019), polarisasi politik memiliki daya rusak yang lain, yakni “melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi, merusak proses dasar legislatif, memperburuk intoleransi dan diskriminasi, mengurangi kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan di berbagai lapisan masyarakat.”
Dari Polarisasi ke Konsolidasi
Kasus-kasus polarisasi politik yang terjadi di belahan dunia lain, seperti kasus kerusuhan di Capiton Hill, Amerika Serikat pada 6 Januari 2021 yang disebabkan oleh para pendukung Donald Trump dalam Pemilu AS 2020 dan kericuhan di Brasil akibat para pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyerbu gedung Kongres, Istana Kepresidenan, dan Mahkamah Agung di ibu kota Brasilia pada 8 Januari 2023, seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia.
Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Indonesia, karena presedennya telah ada, yakni kerusuhan pada aksi demonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 pada 21-22 Mei 2019 yang menyebabkan delapan orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka.
Agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia, mitigasi harus dilakukan sesegera mungkin dengan melipatgandakan konsolidasi kebangsaan, yakni membumikan pemikiran dan memasifkan gerakan kebangsaan untuk semakin mempererat ikatan persaudaraan antarsemua anak bangsa. Melipatgandakan konsolidasi kebangsaan tersebut mengharuskan pelaksanaan tiga agenda strategis kebangsaan.
Pertama, konsolidasi kebangsaan di tingkat elite, terutama elite partai politik yang memang terlibat langsung dalam agenda-agenda politik elektoral. Dalam struktur politik Indonesia, elite memiliki posisi dan peran penting sebagai simpul kelompok masyarakat, yang karena kapasitas, kemampuan dan status sosialnya dapat mengarahkan dan bahkan menentukan pilihan-pilihan politik masyarakat.
Oleh karena itu, konsistensi elite dalam mewacanakan politik kebangsaan dengan menghindari strategi politik identitas dengan kebencian akan berkontribusi signifikan terhadap keharmonisan dan keteduhan iklim demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Kedua, konsolidasi kebangsaan dengan melibatkan pemuda sebagai upaya memangkas generasi politik identitas dengan kebencian. Apalagi, pada Pemilu 2024, pemuda merupakan kelompok strategis yang jumlahnya diprediksi mencapai 54% dari total penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih (CSIS, 2002).
Bagi elite politik, jumlah pemilih muda yang besar tersebut merupakan ceruk suara sehingga isu-isu yang diminati oleh pemuda akan diwacanakan juga oleh elite politik, karena –mengutip Rizal Mallarangeng— politicians go where the voters are. Karena itu, melibatkan pemuda dalam rangka memangkas generasi politik identitas dengan kebencian berarti juga menutup kemungkinan penggunaan politik identitas oleh elite politik.
Ketiga, menciptakan narasi tanding (counter-narrative) terhadap narasi politik identitas dengan kebencian di media sosial dengan narasi-narasi kebangsaan yang menyejukkan dan mencerdaskan sehingga jagat media sosial dipenuhi dengan narasi yang memperkuat demokrasi Indonesia. Oleh sebagian kalangan, mencipatakan narasi tanding ini disebut sebagai bagian dari jihad algoritma.
Dengan pelaksanaan tiga agenda strategis untuk melipatgandakan konsolidasi kebangsaan tersebut, harapannya terjadi shifting dari polarisasi politik ke konsolidasi kebangsaan di tahun politik ini, sehingga perpecahan dan keterbelahan masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama tidak terjadi.