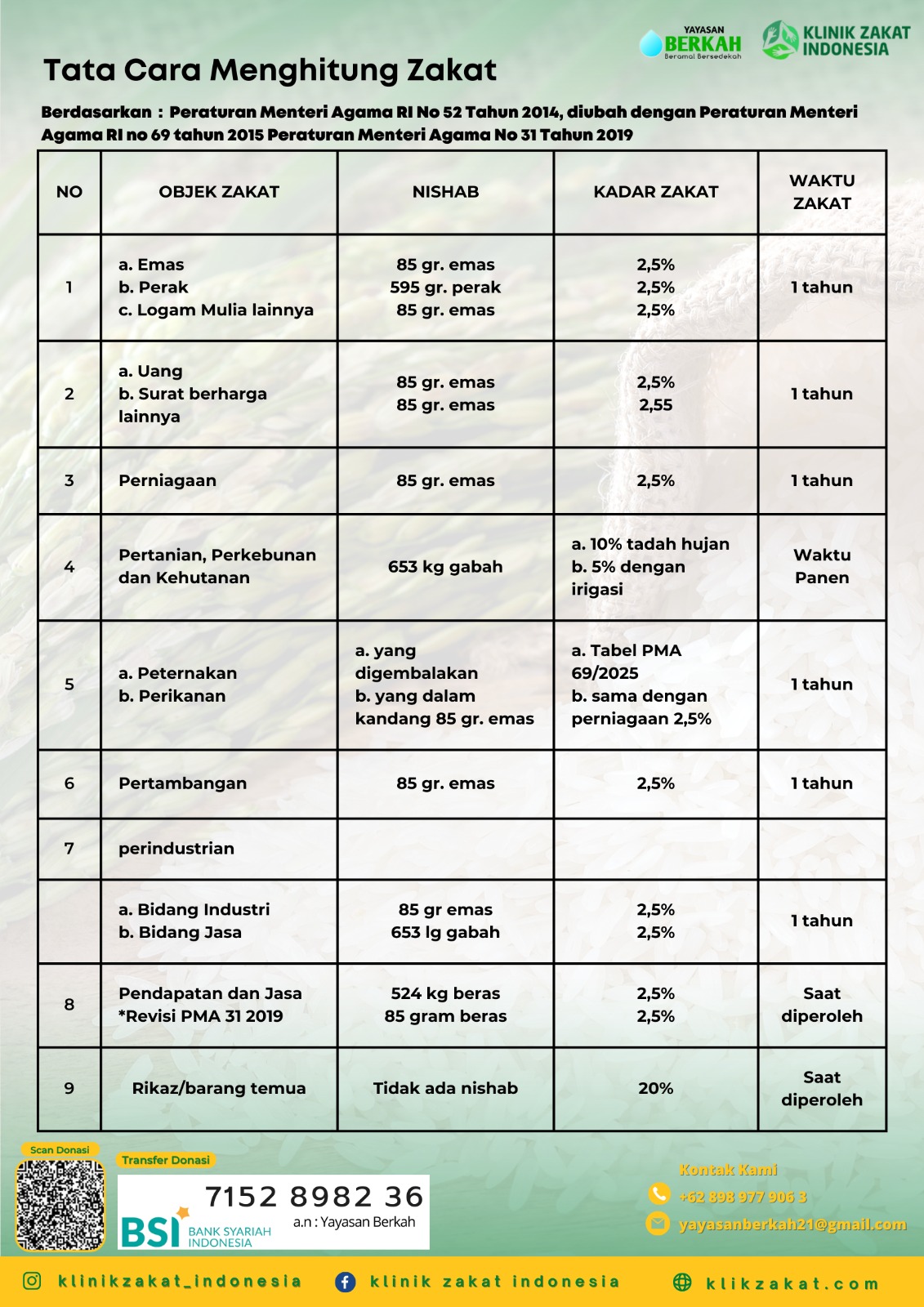Pada 13 Maret, Sarath Weerasekara, Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang pemakaian burqa dan menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam di negara tersebut. Menteri tersebut pernah mengatakan bahwa “burqa” merupakan “simbol ekstremisme agama” dan memiliki “dampak langsung terhadap keamanan nasional”.
Berita tersebut tersebar di kancah internasional dan menuai banyak kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan perwakilan khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, Ahmed Shaheed, serta dari duta besar Pakistan untuk Sri Lanka. Tiga hari kemudian pemerintah menarik kembali pernyataan Weerasekera. Juru bicara cabinet, Keheliya Rambukwella, mengumumkan bahwa keputusan tersebut “membutuhkan waktu” dan proses diskusi yang panjang.
Pengumuman larangan burqa memantik kemarahan umat Islam di Sri Lanka. Mereka melihatnya sebagai serangan terhadap komunitas mereka.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial dengan alasan memerangi ekstremisme. Kebijakan ini semakin mengintimidasi penduduk Muslim dan mengabaikan prinsip-prinsip supremasi hukum.
Gerakan anti-Muslim
Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, di Sri Lanka memang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara mayoritas penganut Buddha Sinhala yang merupakan 70 persen dari populasi dan minoritas Hindu dan Kristen Tamil, yang berjumlah sekitar 12 persen. Selama perang antara pasukan militer dan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), minoritas lainnya di negara ini seperti Muslim, yang berjumlah sekitar sembilan persen dari populasi, jarang menjadi sasaran serangan kelompok ultra-nasionalis Buddha Sinhala.
Setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 2009, gerakan anti-Muslim yang diprakarsai oleh Bodu Bala Sena (BBS), dengan biksu Galabod Aththe Gnanasara sebagai pimpinannya, mulai muncul. BBS adalah kelompok aktivis yang dipimpin oleh biksu Buddha untuk melawan yang mereka sebut sebagai “separatisme sosial” dari kalangan “Muslim ekstremis”. Namun, definisi mereka tentang ekstremisme tampaknya mencakup sebagian besar praktik sehari-hari umat Islam.
Dalam demonstrasi dan kampanye media sosial, BBS selalu keras menggunakan ujaran kebencian terhadap Muslim di seluruh negeri. Hasutan yang dilakukan oleh BBS dan penanaman sentimen anti-Muslim selama beberapa tahun pasca perang saudara juga menyebabkan terjadinya serangan terhadap komunitas Muslim kecil pada tahun 2014, 2017 dan 2018. BBS seolah meniru kelompok Buddha di Myanmar.
Setelah insiden ini, pemerintah daerah tidak mengambil tindakan serius terhadap BBS dan kelompok lainnya dan dalam beberapa kasus menyalahkan Muslim atas kekerasan tersebut.
Pada 2019, kebencian anti-Muslim meningkat lebih lanjut setelah delapan pelaku bom bunuh diri yang berjanji setia kepada ISIS meledakkan diri di gereja, hotel, dan lokasi lain di seluruh negeri pada Minggu Paskah. Ada bukti kegagalan intelijen dan kelalaian di pihak kepemimpinan politik. Namun, liputan media tentang peristiwa tersebut dan kebijakan pemerintah setelahnya lebih banyak menargetkan umat Islam di negara tersebut.
Sayangnya, para ahli jarang menyebut peran gerakan anti-Muslim sendiri sebagai asal mula munculnya paham radikal di kalangan Muslim lokal. Sebut saja Umat Islam di Sri Lanka dalam keadaan terdesak dengan banyaknya hujatan dari gerakan anti-muslim. Umat Islam dengan kondisi terjepit seperti ini tentunya secara psikologis akan meresponnya dengan sikap reaksioner.
Pada bulan Mei, pasca pemboman, terjadi serangan balasan terhadap komunitas Muslim di barat laut Sri Lanka. Ironisnya, respon pemerintah terhadap serangan tersebut sangat dingin. Pemerintah hanya merangkul gerakan BBS yang anti-Muslim. Sementara itu, aparat keamanan memulai penangkapan menyeluruh terhadap para tersangka pengikut kelompok yang bertanggung jawab atas pemboman gereja tersebut.
Sejak itu, beberapa tokoh Muslim terkemuka juga menjadi sasaran tuduhan sewenang-wenang pemerintah. Mereka ditangkap tanpa bukti kuat yang dapat menunjukkan kesalahan mereka. Misalnya, pada April 2020, polisi menangkap Hejaaz Hisbullah, seorang pengacara, karena dicurigai membantu para penyerang di Minggu Paskah. Kemudian pada Mei 2020, Ahnaf Jazeem, seorang penyair muda Muslim, juga ditahan dengan dalih yang sama. Baru-baru ini, mantan pimpinan Jamati Islami, Hajjul Akbar ditangkap dan ditahan untuk kedua kalinya, lagi-lagi tanpa tuntutan yang jelas.
Setelah serangan Minggu Paskah, komite pengawas sektoral parlemen untuk keamanan nasional dibentuk untuk membuat peraturan-peraturan pencegahan terorisme. Komite ini telah membuat beberapa rekomendasi di 14 bidang, banyak di antaranya, berisi kebijakan yang mengekang hak-hak agama minoritas Muslim.
Larangan burqa dan penutupan sekolah Islam berasal dari rekomendasi dari komite ini, seperti halnya beberapa kebijakan lain yang baru-baru ini dikeluarkan. Pada awal Maret, pemerintah mengumumkan bahwa semua buku Islam yang diimpor ke Sri Lanka perlu mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan.
Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan menetapkan beberapa peraturan yang tidak adil. Peraturan tersebut diberi sub-judul “Deradikalisasi terhadap ideologi agama ekstremis yang kejam” yang dibuat di bawah Undang-Undang Pencegahan Terorisme. Peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi aparat keamanan untuk menangkap orang dan mengirimkannya ke pusat rehabilitasi untuk “deradikalisasi” selama satu tahun tanpa perlu proses tambahan.
Terlepas dari hal di atas, pemerintah telah mencari cara lain untuk mengintimidasi umat Islam di negara tersebut. Ketika pandemi COVID-19 menyebar ke Sri Lanka pada musim semi 2020, pemerintah memberlakukan kebijakan kremasi wajib bagi korban COVID-19 dan menolak mengizinkan umat Islam untuk menguburkan jenazah sesuai dengan keyakinan agama mereka.
Umat Islam yang menyarankan penguburan jenazah dianggap sebagai sebagai umat yang memiliki sentimen “kesukuan” dan paham “terbelakang”. Lebih dari itu, pemerintah menyebut penguburan jenazah Covid-19 sebagai perilaku tercela di tengah keadaan darurat kesehatan masyarakat. Meskipun ada kecaman di dalam dan luar negeri dan meski ada pedoman yang disebarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang menekankan amannya penguburan, pemerintah tetap mempertahankan posisinya selama hampir satu tahun ini. Penguburan baru diizinkan baru-baru ini di bawah tekanan internasional.
Sentimen Anti-Islam Sebagai Strategi Pemilu
Elit politik di Sri Lanka untuk memenangkan pemilihan jelas akan menimbulkan permusuhan etnis-agama. Setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 2009, ketika kemenangan terhadap perlawanan Macan Tamil cukup dibanggakan oleh pemerintah, permusuhan terhadap semua minoritas lainnya dan terutama Muslim dipupuk dengan semangat baru.
Keluarga Rajapaksa, yang mendominasi kancah politik di Sri Lanka sejak 2005, terlibat dalam penanaman sikap ini sampai akhirnya mereka kalah dalam pemilihan umum 2015. Selama kampanye politik mereka setelah 2015, partai baru Rajapaksa yang bernama Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) menggaet para biksu ekstremis dan pendukung gerakan anti-Muslim.
Retorika terkait meningkatnya bisnis Umat Islam sebagai yang akan mengancam pengusaha dari kalangan penganut Buddha Sinhala, isu konspirasi mereka untuk mengalahkan mayoritas Sinhala, penyematan teroris kepada setiap penganut agama Islam selalu digunakan secara luas di Sri Lanka untuk menyudutkan Umat Islam.
Pada Oktober 2018, Rajapaksa mengalami kemunduran yang signifikan. Mantan presiden dan anggota parlemen Mahinda Rajapaksa yang berkolusi dengan Presiden Maithripala Sirisena melancarkan kudeta untuk mengambil kendali pemerintah. Namun mereka dikalahkan ketika Mahkamah Agung mencabut klaim mereka atas legitimasi dan akibatnya pamor Rajapaksa mengalami penurunan.
Pengeboman tahun 2019 menyemangati politik keluarga Rajapaksa dan membantu mereka mengatasi ketidakpopuleran sesaat yang mereka perjuangkan. Rajapaksa berusaha memanfaatkan pemboman untuk keuntungan politik mereka. Mereka menuduh rezim yang berkuasa berkonsentrasi pada rekonsiliasi dengan minoritas dan mengabaikan keamanan. Ketika beberapa bulan kemudian, Gotabaya Rajapaksa, saudara laki-laki Mahinda Rajapaksa, dicalonkan sebagai calon presiden SLPP, ia menyatakan di platformnya: “Tugas utama saya adalah memastikan bahwa tanah air kita yang sekali lagi terancam oleh unsur teroris dan ekstremis aman dan terlindungi.”
Dengan menggunakan retorika anti-minoritas dan pro-keamanan dalam kampanyenya, Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden dengan persentase suara Buddha Sinhala yang tertinggi dan menunjuk saudaranya, Mahinda, seorang mantan presiden sebagai perdana menteri. Sejak saat itu, di setiap kesempatan, presiden telah menegaskan kembali komitmennya kepada mayoritas Buddha ini dan menegaskan kebijakannya untuk memerangi ekstremisme Islam. Saat ini, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti-Muslim.
Dalam konteks ini, kebijakan anti-Muslim ini sebenarnya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintahan Rajapaksa. Pemerintah Sri Lanka saat ini sedang menuai kemarahan publik atas penipuan pajak secara besar-besaran, meningkatnya penolakan terhadap izin penebangan hutan, dan meningkatnya kecemasan publik atas kemerosotan ekonomi. Nampaknya gerakan anti-Muslim yang digaungkan pemerintah ini akan meningkat jika popularitas pemerintah sendiri terus menerus merosot.
Tetapi kebijakan anti-Muslim yang dikeluarkan pemerintah malah mungkin akan menjadi bumerang. Pada bulan Maret, pemerintah Sri Lanka mengalami kekalahan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). PBB mengeluarkan resolusi dengan menugaskan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi serta bukti kejahatan perang yang dilakukan selama perang saudara. Mosi tersebut dilakukan karena hilangnya dukungan untuk pemerintah dari beberapa negara mayoritas Muslim. Mereka abstain dari pemungutan suara.
Resolusi tersebut merupakan akibat dari perlakuan pemerintah terhadap Umat Islam di Sri Lanka dan marjinalisasi yang terus berlanjut terhadap kelompok minoritas.
Ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk memobilisasi konstituennya, yang diperparah dengan permusuhan etnis-agama, merupakan warisan gelap politik pasca-kemerdekaan Sri Lanka yang tampaknya akan berlanjut dalam jangka panjang. Resolusi UNHRC untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang di Sri Lanka merupakan perkembangan yang perlu disambut baik. Namun demikian, prospek masa depan minoritas di negara ini tetap suram. Sepuluh tahun setelah perang saudara, pemerintahan Sri Lanka harusnya belajar dari masa lalunya, bukan malah memperkeruh suasana dengan meningkatkan sentimen anti-Muslim.