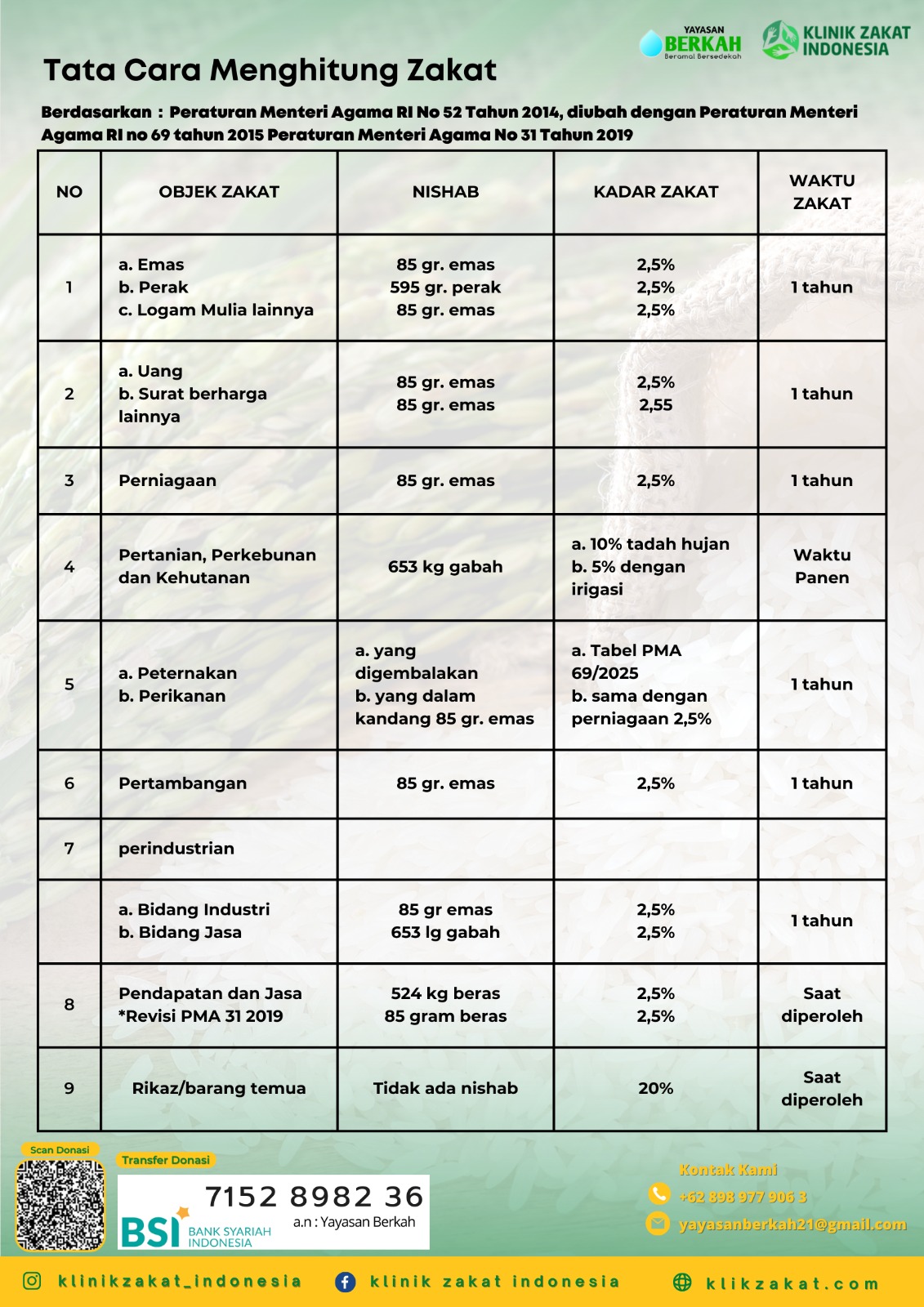Catatan : Rami Musrady Zaini
DALAM konteks transisi demokrasi, kiranya relevan kutipan bijak bahwa penderitaan adalah harga dari proses sebuah pembelajaran. Syahdan, kutipan itu diucapkan dalam sebuah drama yang ditulis oleh penyair drama Athena, Aeschylus, yang diproduksi pada tahun 458 SM – tahun ketika warga Athena mengorbankan perang brutal di dua front. Oleh sejarawan terkemuka asal Inggris, Arnold Toynbee, kebrutalan itu diidentifikasi menjadi masa sulit dan masa yang menimbulkan penderitaan.
Peradaban Jepang, India, china, dan Yunani yang sebenarnya pernah berada pada titik jenuh yang diwarnai dengan penderitaan-penderitaan, pada akhirnya memantik gerakan restorasi bahkan revolusi sebagai proses naturalisasi terhadap watak realitas masyarakatnya. Jika di komparasikan dengan konteks Ke-butonan kita saat ini, sebagai masyarakat yang arif dalam memaknai setiap etape perjalanan maka keberulangan sejarah itu sejatinya harus dijadikan pemantik kesadaran kita untuk berbenah.
Masih segar di ingatan kita tentang sebuah peristiwa heroik warsa 2003 dimana masyarakat secara kolosal turun ke jalan hanya untuk menjemput ‘harapan besar’ bernama otonomi yang kemudian diverbalkan menjadi pemindahan administrasi daerah dari Baubau menuju Pasarwajo. Ada, semangat dan gerakan hati untuk merebut itu, kalau dilihat lebih mendalam harapan dalam gerakan itu hanyalah untuk sebuah alasan yakni ‘perubahan’.
Saat itu dengan kesadaran kolektif temporer yang tak berbasis ideologi, masyarakat percaya bahwa Otonomi daerah adalah sebuah janji perubahan. Sayang semua berbuah retak, peralihan kekuasan ke ke kuasaan lain tidak membawa kemaslahatan bersama, juga tidak dapat membangkiktan kearifan lokal masyarakat. Yang tertinggal hanyalah utang otonomi yang tak pernah lunas.
Membayangkan Buton Utara, Konawe Utara, Konawe Kepulauan sebagai prototip perubahan yang massif dalam perhelatan pilkada lalu adalah sebuah contoh yang coba kita sandingkan. Kemasifan tersebut tidak lain adalah karena dipicu oleh kesamaan visi dan terdapatnya musuh bersama (common enemy) yang harus ditaklukan ditambah Kecendrungan untuk mengelola daerahnya sendiri adalah elan vital dari gerakan masyarakat yang saya cantumkan diatas. Mereka berhasil mendudukan orang-orang yang paham dan mengerti akan daerahnya sendiri. Ini juga bisa berarti kita hanya menjadi penonton akhir dari daerah-daerah baru yang telah berbenah dengan kualitas otonomi daerahnya.
Idealita masyarakat Buton saat ini tentunya sangat jauh berbeda dengan ketiga kabupaten tersebut, masyarakat mereka sangat sadar dan tersadarkan oleh sebuah pemaknaan bahwa Otonomi adalah hak masyaratnya untuk turut andil dalam pembangunan dan berdemokrasi.
Sementara idealita masyarakat kita saat ini cukup terlukiskan dengan apa yang dikatakan oleh Jean-Jacques Rouseu sebagai ‘amour-propre’ atau ‘spirit individualistis.’
Idealita Amour-propre telah menenggelamkan masyarakat hingga ke struktur yang terdalam, menyandera moral masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan tatanan sosial menjadi rusak. Kepentingan Individu lebih menguasai ketimbang berpikir kolektif untuk kemajuan daerah.
Alhasil masyarakat semakin tercerabut ke dalam siklus budaya yang disebut sebagai sistem nilai indrawi (Sorokin) yaitu keadaan ketika secara kolektif, logika material menjadi nalar sosial dan fenomena spritual dinisbikan oleh realitas materi. Materi dan nilai indrawi menjadi logika utama dalam setiap tindakan sosial yang hadir dalam ruang kebutonan kita hingga detik ini.
Relasi ‘spirit individualistis’ dan ‘sistem nilai inderawi’ menjadi gelombang fragmentasi sosial yang pada gilirannya mencerabut akar budaya kita, hal ini diperparah lagi oleh pertentangan identitas masyarakat lokal antara ‘orang dekat kuasa’ dengan ‘orang tak dekat kuasa’ baik secara komunal maupun individu yang gejalanya cenderung mempertahankan ‘status quo’ dengan menutup mata pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di daerahnya.
Bahkan relasi ini juga dilakukan oleh kaum-kaum pemodal dan intelektual, yang penting Pangkat, Jabatan, dan Kue pembangunan ternikmati. Padahal jika ditilik golongan intelektual ini cukup mengisi struktur mobilitas vertikal yang cukup mumpuni untuk menggagas visi perubahan. Relasi itu dicirikan dengan tidak berfungsi dan kuatnya lembaga yang mereka pimpin, kebanyakan hanya sibuk membebek ke mana arah kuasa melangkah. Sayang Jiwa-jiwa mereka telah terpenuhi dengan kebutuhan sitem indrawi, sama dengan halnya jiwa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-hasanah was sayyi’ah “Jiwa yang dipenuhi dengan kecintaan pada pangkat dan jabatan.”
Maka, Jabatan Pun berubah menjadi jembatan menggerogoti masyarakatnya sendiri. Sehingga terkadang mereka tak mau lagi berbenah, dan cenderung mengambil jalan tengah. Tak heran jika setiap massa kekuasaan ‘mereka’ selalu ada dan hidup diatas keterbelakangan sosial masyarakatnya.
Warsa ini, yang perlu dilakukan dalam menuju era peralihan adalah kesepahaman, konsensus, dan kesadaran dalam bentuk kontrak sosial yang didasari nilai bahwa kita benar-benar terbelakang. Soekarno menyebutnya dengan ‘Die Umwertung Aller Werte,’ penjungkirbalikkan semua nilai.
Membongkar seluruh kontrak sosial lama yang telah tertanam di benak masyarakat dan membuat kontrak-kontrak sosial baru yang lahir dari kebijkan intelektual manusia, dengan demikian apabila hendak merubah kontrak sosial yang ada, hanya dapat dilakukan dengan eksplorasi kebijakan intelektual manusia yang pangkalnya ada pada kesadaran manusia yang membentuknya. Karena sebenarnya Ikatan-ikatan kelompok manusia, baik dalam lingkup yang sederhana seperti ikatan kesukuan maupun dalam skala yang lebih luas seperti Negara, pada prinsipnya adalah hanya sebuah ‘kontrak sosial’ saja, mengambil teori dari Jean J. Rosseau.
Perubahan besar yang tidak bangkit dari kesadaran, dimanapun dan kapan pun, pasti berujung pada kekecewaan atau sebaliknya hasil suatu gerakan perubahan harus ditumbangkan lagi oleh perubahan yang lain. Di era peralihan, ketika masyarakat makin matang dalam berdemokrasi, maka seorang yang mampu menjembatani sebuah kontrak sosial baru yang akan menjadi satu-satunya harapan melakukan aspirasi. Dan kepemimpinan ideologislah (memiliki nilai) adalah satu-satunya harapan untuk mewujudkan tatanan nilai yang menuju visi perubahan, sebab dengan seorang yang berideologilah jalan menuju perubahan itu akan terbuka lebar.
Periode peralihan seperti metamorfosis ulat menjadi kepompong, sebelum sempurna menjadi kupu-kupu yang indah, terkadang mesti bertabur perih. Dan pada periode ini harus dilalui dengan komitmen dan konsistensi pada konsensus kita bersama dalam bentuk kontrak sosial baru. Jika tidak demikian, maka segala perjuangan kita akan bersifat pasif. Kita tidak akan dapat melampaui taraf saat ini dan kita hanya akan meningkat dari tingkat statis yang satu ke tingkat statis yang lain. Lima belas tahun sudah cukup bagi kita untuk belajar