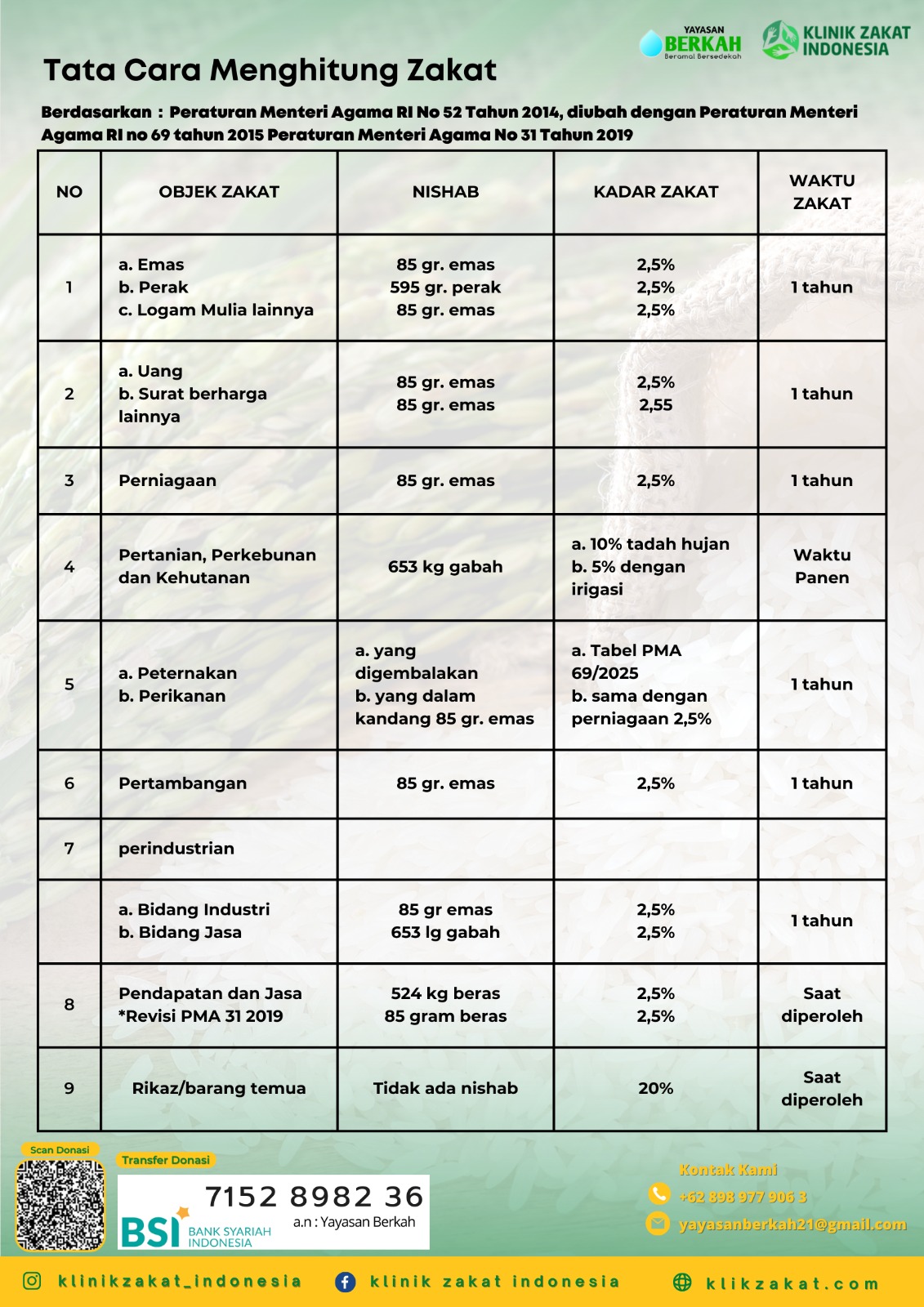Satu dekade pasca pemberontakan melawan Muammar Khadafi pada 17 Februari 2011, Libya hancur lebur akibat konflik bersenjata, dan makin diperparah dengan intervensi kekuatan asing dan perpecahan faksi di Dewan Keamanan PBB.
Pada 17 Februari 2011, di Benghazi, setelah dua hari demonstrasi menuntut pembebasan seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia Fathi Terbel, 600 orang berkumpul di depan kantor polisi utama kota. Para demonstran ditindas dengan kejam. Penindasan ini tidak dapat menghentikan proses demonstrasi. Polisi meninggalkan kota dan rezim Khadafi dari Tripoli dan berjanji menghukum rezim Benghazi. Lalu dengan sangat cepat, pemberontakan menyebar ke beberapa penjuru kota di Libya timur.
Bala bantuan dikirim dari Tripoli ke timur tetapi dapat dihentikan di Ras Lanouf, wilayah bulan sabit minyak, sekitar 600 kilometer dari Benghazi. Tentara dan pemberontak bertempur di wilayah ini selama beberapa minggu. Di Misrata, juga terjadi pertempuran antara kekuatan rezim dan kaum revolusioner yang mengangkat senjata.
Pada 17 Maret 2011, di Dewan Keamanan PBB, masyarakat internasional (Chomsky menyebutnya negara-negara Barat) menggunakan resolusi 1973. Resolusi ini memungkinkan intervensi militer di Libya dan memberlakukan zona larangan terbang di atas negara ini serta “melindungi penduduk sipil Libya.” Koalisi ini, yang dipimpin oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, melakukan ratusan serangan yang menargetkan rezim Khadafi.
Pada tanggal 20 Agustus 2011, kaum revolusioner bersenjata memasuki Tripoli tempat Muammar Khadafi dan anggota rezimnya yang berpengaruh melarikan diri. The “Guide” menetap di Sirte, wilayah tempat pertempuran terus berlanjut. Pada 20 Oktober 2011, pesawat Amerika dan Prancis menabrak konvoi Muammar Khadafi yang berusaha meninggalkan Sirte. Rezim Khadafi tumbang.
Selain Muammar Khadafi dan salah satu putranya, sekitar 80 pejabat rezim segera dilikuidasi oleh kaum revolusioner, dibantu oleh angkatan udara NATO.
Jatuhnya rezim Kolonel Muammar al-Khadafi di Libya, setelah 42 tahun berkuasa, telah menenggelamkan negara ini ke dalam lembah kekerasan dan penderitaan yang mematikan selama satu dekade. Perebutan kekuasaan dan legitimasi oleh berbagai kelompok yang ingin berkuasa pun tak terelakkan.
Aktor-aktor, yang dulunya dibungkam dan dipenjara di era kekuasaan dictator Khadafi, kemudian mencoba untuk menaklukkan kekuasaan. Beberapa perang terjadi, merusak impian demokrasi. Libya terlibat dalam konflik bersenjata, yang dipicu oleh campur tangan asing berikut dengan kepentingannya yang saling kontradiktif. Alih-alih demokrasi yang ingin ditegakkan, Libya tenggelam dalam kubangan perang tiada henti.
Islamis Libya Berambisi Merebut Kekuasaan
Seperti negara-negara lainnya yang mengalami revolusi “Musim Semi Arab”, pemberontakan di Libya dimulai dengan munculnya protes dari gerakan Islamis, yang didukung oleh Amerika Serikat (lihat misalnya email Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika, yang disiarkan di situs web AS Departemen Luar Negeri pada tahun 2020. Email ini dengan jelas menunjukkan hubungan Clintons dengan Islamis di Libya serta di Mesir dan Tunisia).
Tak hanya itu, gerakan Islamis ini secara finansial dibantu oleh Qatar dan propaganda medianya, al-Jazeera. Sebagai akibatnya, partai-partai politik Islam di Libya, dari semua lapisan masyarakat, dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrim, bergabung merebut kekuasaan.
Para Islamis, yang sebagian besar dipenjara pada masa Khadafi, dibebaskan setelah serangan NATO. Sebagian besar para Islamis ini berpartisipasi dalam konflik bersenjata sebagai “revolusioner 17 Februari.” Para revolusioner ini menganggap kekuasaan di Libya harus kembali kepada tangan mereka secara de facto.
Mereka merasa sebagai kelompok yang berhak mendapatkan kekuasaan karena telah “mengorbankan” diri mereka di medan perang. Begitulah cara pandang para Islamis dalam dua kali pemilu. Mereka menolak hasil pemungutan suara pemilu pada tahun 2012 dan 2014 dengan menggunakan senjata.
Pada tahun 2012, kelompok Islamis memainkan peranan yang cukup signifikan dalam pemilu. Mereka membentuk beberapa partai politik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, kemenangan kaum liberal dalam pemilihan umum demokratis pertama yang diselenggarakan di Libya selama setengah abad sangat mengejutkan mereka.
Pada tahun 2012, harapan rakyat Libya akan perubahan politik sangatlah besar. CGN, Kongres Umum Nasional, mengambil alih kekuasaan dan menggantikan CNT, Dewan Transisi Nasional yang dibentuk pada tahun 2011 untuk mengelola negara dan memastikan transisi. Dengan sangat cepat, CNT ditempatkan di bawah kategori kaum Islamis. Kongres Umum Nasional menaruh kepercayaannya pada pemerintahan Ali Zaidan, namun hal ini bukannya tanpa adanya kesulitan. Dua tahun kemudian, pada tahun 2014, Zaidan dipaksa mengundurkan diri dan membiarkan negara tersebut di bawah ancaman kehancuran.
Pemilu Legislatif 2014
Pada 25 Juni 2014, pemilihan legislatif baru berlangsung dan sekali lagi kaum liberal dan independen memenangkan pemungutan suara. Padahal, butuh waktu beberapa minggu untuk mengumumkan hasilnya.
Pada bulan Juli, milisi Misrata, yang bersekutu dengan kelompok bersenjata lain dari Ikhwanul Muslimin, dari kota-kota lain di Libya barat, menyerbu ibu kota untuk mengusir milisi non-Islam dari Zintane. Operasi itu disebut Subuh Libya (“fajar Libya”). Sasaran utamanya adalah bandara internasional yang terletak di bukit strategis. Kekuatan ini kemudian memperluas kekuasaan mereka ke wilayah ibu kota, Tripoli, lalu melebar ke bulan sabit minyak.
Parlemen Libya yang lahir dari pemilu 2014 dan masih menjalankan fungsinya hingga hari ini melarikan diri ke wilayah timur negara tersebut. Parlemen menunjuk pemerintah yang pindah ke Al-Bayda di wilayah timur Libya karena alasan keamanan dan agar dapat mengadakan pertemuannya jauh dari ancaman kaum milisi. Parlemen sendiri juga menetap di timur, di Tobruk.
Di wilayah barat Libya, pemerintahan lain kemudian dibentuk oleh para Islamis dan milisi di Tripoli. Pemerintahan kaum Islamis ini bertahan sampai dibentuknya pemerintahan Fayez el-Sarraj, pada Maret 2016, menyusul perjanjian Skhirat yang ditandatangani pada akhir 2015. Tujuan dari perjanjian politik ini adalah untuk menyatukan pemerintah Libya, tetapi berdampak sebaliknya: adanya dua pemerintahan wilayah timur dan barat ini dan keduanya masih eksis sampai sekarang.
Khalifa Haftar dan Keinginan untuk Membentuk Kekuatan Militer
Marsekal Khalifa Haftar berambisi memimpikan kekuasaan. Namun pertanyannya apakah sosok ini ingin meniru Muammar al-Khadafi atau meniru pemerintahan Mesir? Bagaimanapun, Haftar lebih memilih sistem otoriter daripada demokrasi. “Rakyat Libya belum siap untuk demokrasi,” slogan yang terus-menerus ia ulang-ulang dalam berbagai kesempatan.
Pada tahun 1980-an, Khalifa Haftar merupakan seorang jenderal di tentara Libya di bawah rezim Khadafi. Pada tahun 1990, ia mengasingkan diri di Amerika Serikat, setelah melakukan beberapa upaya untuk menggulingkan Kolonel Khadafi dengan dukungan CIA.
Haftar kembali ke Tripoli setelah pemberontakan 2011 dan mengambil bagian dalam pertempuran melawan pasukan Khadafi di Libya timur, di mana dirinya mendapatkan legitimasi politik dan kekuasaanya. Haftar mendirikan Tentara Nasional Libya (ANL), yang sebagian besar terdiri dari tentara rezim sebelumnya. Kemudian, ANL memasukkan brigade Islamis Salafi (namun Islamis ini anti-Ikhwan Muslimun) ke dalam barisannya. Dalam praktiknya, berbagai sepak terjangnya di Libya tidak berbeda jauh dari milisi-milisi dari Barat.
Pada tahun 2014, Khalifa Haftar meluncurkan operasinya yang bernama al Karama “kemuliaan” untuk “menyingkirkan kelompok ekstremis Islam di Benghazi”. Pada kenyataannya, prajurit ini ingin tampil sebagai benteng melawan kaum Islamis. Pasukan yang dipimpin Haftar ini mendapat dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab dan Rusia. Ia hanya butuh waktu tiga tahun untuk merebut kembali kota dan menggempur beberapa gerakan ekstremis, seperti Ansar al-Sharia dan kelompok revolusioner di Benghazi. Pada 2016, Haftar juga mengambil alih bulan sabit minyak dan kemudian mulai berperang melawan ekstremis di Derna.
Pada April 2019, setelah mendapat persetujuan diam-diam dari Amerika, Haftar berusaha menaklukkan Tripoli, yang secara resmi berada di bawah pemerintahan Fayez el-Sarraj, tetapi pada kenyataannya berada di bawah kendali milisi Islam.
Khalifa Haftar tiba di gerbang Tripoli, tetapi gagal merebut ibu kota Libya tersebut dan berulang kali menolak berdamai dengan Fayez el-Sarraj, di Kairo, Abu Dhabi, Paris, Moskow dan terakhir di Berlin pada Januari 2020. Ketika Perancis mengumumkan kesepakatan untuk pemilihan akhir tahun pada 2019, pendukungnya berkampanye agar dirinya menjadi kepala negara. Salah satu cara untuk memenangkan pemilihan.
Secara umum, menurut pengakuan PBB, batas waktu pemilihan ini sangat pendek dan hampir tidak mungkin untuk diselenggarakan. Pada Mei-Juni 2020, dengan bantuan pesawat tak berawak Turki, milisi yang menguasai Tripoli melakukan serangan balik dan memukul mundur pasukan pro-Haftar hingga ke Sirte.
Kesalahan Dunia Internasional di Libya
Dalam bukunya “A Promised Land”, Barak Obama, mantan presiden AS, mengakui bahwa intervensinya di Libya merupakan kesalahan terbesar selama dua masa jabatannya. Dan dengan alasan yang sama, masyarakat Internasional dengan cepat melepas tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya di Libya.
Lebih buruk lagi, 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah soal Libya. Orang Eropa juga. Pemerintahan Trump memiliki kebijakan yang multi. awalnya, Trump sangat pro-Haftar lalu beralih mendorong Turki untuk menetap di Libya melawan Rusia. Sementara itu, tentara bayaran Rusia Wagner mendukung Khalifa Haftar. Turki memang memperkuat peranan militer dan ekonominya di Tripoli.
Harus dikatakan bahwa Libya mewakili posisi strategis di Afrika. Libya memiliki cadangan minyak terbesar di benua itu dan cadangan gas yang sangat besar di Mediterania timur. Sejak Perang Dunia Kedua, kekayaannya banyak diincar oleh kekuatan besar dan, baru-baru ini, oleh kekuatan regional.
Ketidakberdayaan PBB
Selama sepuluh tahun, perpecahan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempersulit pencarian solusi politik di Libya. Ghassan Salamé Lebanon, mantan perwakilan khusus dari sekretariat jenderal PBB, mengecam negara-negara ini.
Tetapi, sekali lagi, PBB tidak pernah selalu konsisten dengan dirinya sendiri. Persetujuan Skhirat, yang diperoleh di bawah naungan PBB pada Desember 2015, telah mengecualikan kamp Khalifa Haftar, serta pendukung rezim sebelumnya.
Kali ini, dari 74 anggota forum dialog Libya yang dilantik sebagai eksekutif baru pada 5 Februari 2021, 42 di antaranya adalah Islamis. Anggota forum semuanya dipilih oleh PBB. Dan Aliansi Pasukan Nasional, sebuah partai liberal dan sekuler yang mendapat popularitas luas, tidak berhak atas perwakilan manapun!
Pada 24 Desember, dewan eksekutif baru yang dihasilkan dari pemungutan suara forum ini hanya memiliki waktu sepuluh bulan untuk menyelesaikan misi yang sangat kompleks, misi melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan pemilihan umum di negara yang sudah terpecah menjadi dua kekuatan. Negara ini menderita karena kehadiran militer asing: Turki dan Rusia. Kalaupun pemilu digelar dengan baik pada 24 Desember, apakah masyarakat internasional dari negara-negara Barat kali ini bisa menjamin hasil pemilu di Libya?
Siapa yang bisa menjanjikan rakyat Libya dengan kedamaian setelah sepuluh tahun jatuhnya rezim Khadafi? Siapa pula yang bisa menjamin bahwa angkatan bersenjata di kedua belah pihak akan mematuhi hasil pemilu?
Terlepas dari secercah harapan yang muncul dari lahirnya pemerintah sementara baru-baru ini, kekacauan Libya tampaknya tidak dapat dengan mudah dicarikan solusinya. Konflik internal antara berbagai kelompok Islamis dan Non-Islamis dan konflik kepentingan antar negara-negara asing di Libya membuat negara ini hancur. Harapan untuk berdirinya demokrasi pun semakin jauh api dari panggangnya.