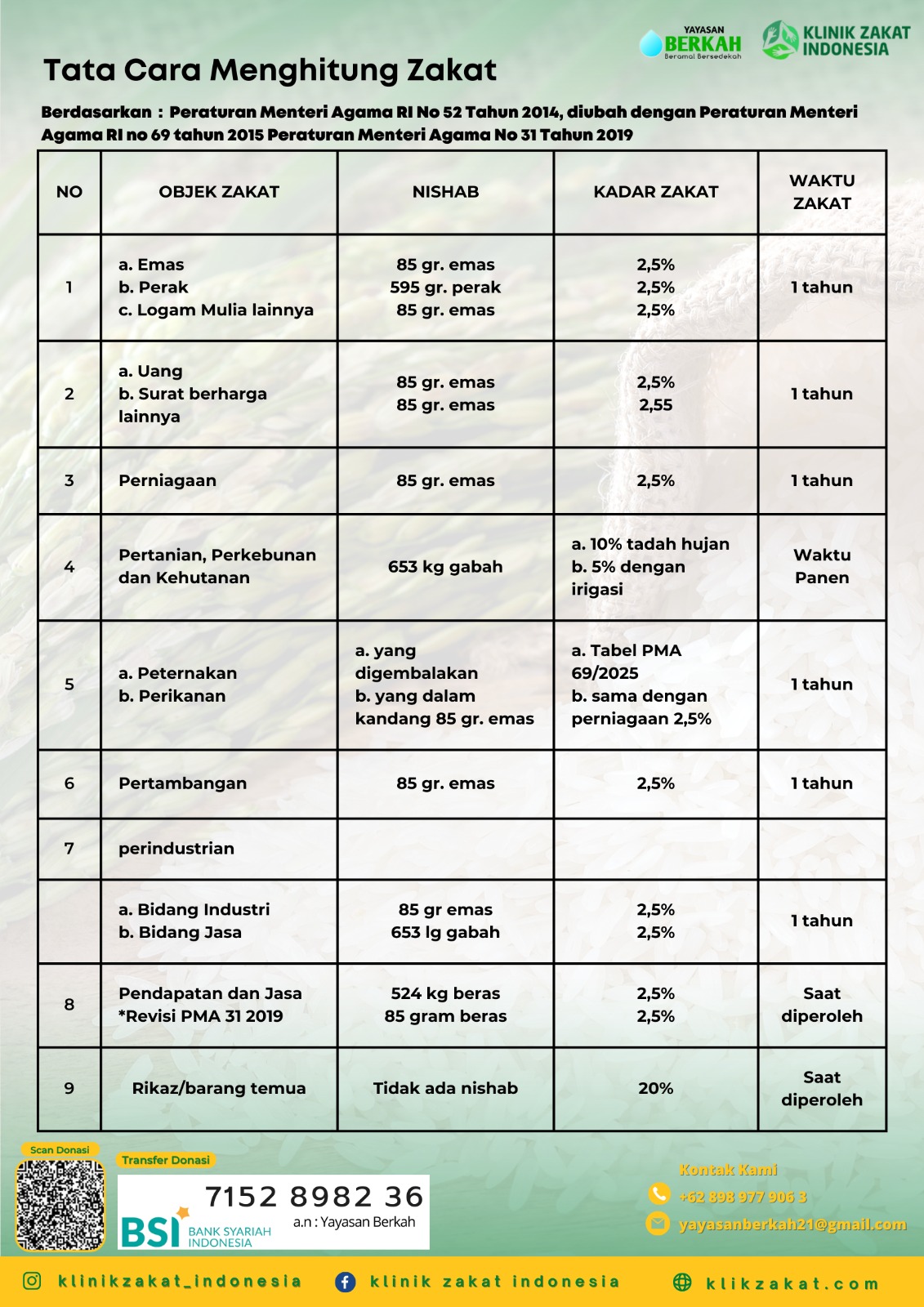Oleh: Fahruddin Faiz (Dosen Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
“In old days books were written by men of letters and read by the public. Nowadays books are written by the public and read by nobody”—Oscar Wilde—
“Times have changed in research and if you are not using Facebook, Twitter, Youtube, Wikipedia, Google, and the like, you will be left in the dark”—Steven Magee—
Sejauh yang aku tahu, tulisan menjadi menarik ketika menginformasikan hal baru, mengungkap hal-hal yang kontroversial dan ‘layak jual’ atau setidaknya memberikan ‘hiburan’ atas waktu senggang para pembacanya.
Ironisnya, aku merasa sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam tiga hal tersebut. Pengetahuan dan wawasan yang kumiliki sama sekali tidak baru, tidak kontroversial dan pasti tidak ‘menghibur’.
Sementara aku berani menjamin: Tiga fungsi itu secara sekaligus telah dijalankan dengan amat tepat oleh makhluk masa kini yang bernama medsos a.k.a. media sosial.
Kalau aku paksakan menulis, maka akan terjadi sebagaimana pepatah jawa: Nguyahi segara, menggarami lautan. Menaburkan garam di lautan, kesia-siaan.
Apapun yang akan aku tuliskan pasti sudah terungkapkan secara jauh lebih panjang lebar dan jauh lebih berkualitas di belantara dunia maya dan media sosial.
Mereka yang nantinya membaca tulisanku kemungkinan hanya ‘orang-orang dekatku’ yang kasihan dan penasaran akan ‘ulah apa lagi yang aku lakukan’.
Jadi, apa manfaatnya tulisanku?
Bukankah kini jutaan kata setiap menitnya dihamburkan oleh sangat banyak orang melalui gawai yang digenggamnya? Suhuf-suhuf WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan semua sejenisnya mengungkap fakta: betapa luas dan kayanya wawasan manusia hari ini.
Jutaan postingan setiap harinya itu merupakan tonggak sejarah, milestone yang mengukuhkan keunggulan manusia sebagai Sang Khalifah alam raya. Manusia, di era yang mereka sebut sendiri sebagai era revolusi industri 4.0, telah begitu rupa meningkatkan derajat dirinya tidak hanya sebagai homo-sapiens, namun juga homo super-sapiens.
Lantas adakah perlunya aku menulis?
Aku hanyalah seorang yang bisanya cuma terkesima, melongo, menyaksikan jingkrak-jingkrak revolusi teknologi yang ditahbiskan sebagai era 4.0 itu.
Akalku sama sekali nggak nyampek. Simbol 4.0 itu mungkin bagi orang lain begitu wow, namun bagiku yang tidak paham, bisa terbaca sebagai bermakna usia 40 (tanda kematangan berpikir) atau skor 4-0 dalam sepak bola (tanda kemenangan mutlak), atau jangan-jangan seperti seorang teman yang membacanya sebagai: keinginan beristeri 4 namun keberanian 0.
Kesimpulannya? Kalau aku paksakan menulis, muatan tulisanku pastilah sesuatu yang tidak nyambung dan kadaluwarsa.
Membaca cuatan dan cuitan kebijaksanaan orang-orang hari ini dalam berbagai media sosial, meskipun kadang hanya satu atau dua kalimat saja, terasa betapa berkualitas dan bermakna kalimat-kalimat itu.
Betapa arif dan bijaksana orang-orang itu. Dari tangan mereka meluncur untaian mutiara-mutiara kehidupan yang begitu berharga. Betapa dalam rahasia hakekat hidup yang mereka tampakkan, betapa pentingnya untaian makna yang terjalin dari gerak jemari mereka.
Bahkan tanpa sadar aku sesekali terhanyut dan manut saja saat diperintah oleh tulisan-tulisan tersebut untuk share dan aminkan.
Share kebajikan-keutamaan, berbagi nikmat-kegembiraan, memberi pelajaran-tuntunan kebenaran, itulah kiranya yang sedang dilakukan oleh banyak orang melalui medsosnya, dan tak mampu sekedar kutirukan.
Bagaimana akan kutiru sementara untuk memahami saja kadang aku harus susah payah, apalagi untuk menjalankan dan mewasiatkannya.
Maqam-ku masihlah hanya murid yang dituntut lebih banyak membaca dan mendengarkan.
Di tengah banyak sekali orang yang seakan berlomba menunjukkan kelebihannya, entah itu kemahiran menyusun kalimat mutiara, kepiawaian mengambil gambar bermakna, atau kecanggihan membuat video petuah:
Diam-diam aku merasa minder dan tidak percaya diri dengan kemampuanku sendiri. Aku sama sekali tidak yakin bahwa wawasan-wawasan yang aku miliki lebih berkualitas dibanding semua itu.
Kadang aku cermati orang-orang berkualitas itu berselisih paham. Argumen berbalas argumen, kritik berbalas kritik, gagasan-gagasan cerdas saling berbenturan.
Betapa semangat mereka berkomitmen kepada kebenaran, hingga sering muncul saling berbalas sindiran, bertukar nyinyiran, sampai tak sadar mengeluarkan caci dan makian, fitnah dan perendahan, demi kebenaran tentunya.
Aku pun merasa menjadi semacam kancil yang kebingungan di tengah para gajah yang sedang berbenturan. Apalah yang kubisa selain minder dan mengakui kenyataan kekuranganku?
Bagaimana aku tidak minder saat suatu ketika membaca postingan seorang anak sekolah dasar: “Kalau engkau sayang padaku harusnya kamu paham dan peduli aku dong!” Bukankah ini gagasan Erich Fromm dalam the art of loving yang kemarin susah-payah aku kaji itu?
Pelajaran apa lagi yang layak kutulis begitu aku dengar tukang ojek online membahas politik dan menutup dengan kalimat: “Politik itu memang tidak ada hubungannya dengan moralitas, mas”.
Kalimat semacam ini dulu di awal modern hanya dapat diungkapkan oleh seorang Machiavelli melalui Il Principle.
Betapa aku shock ketika di suatu pagi seorang ibu mengadu bahwa anak gadisnya yang masih SMP melaporkan bapaknya ke polisi karena malam sebelumnya saat pulang dini hari ia ditampar. Alasan pengaduannya?
Pelanggaran HAM. Bayangkan, isu HAM yang para ahli saja berdebat tanpa keputusan, sudah mampu ditangkap dan diimplementasikan oleh seorang anak SMP.
mengapa aku masih harus menulis?
Suatu ketika Mullah Nasruddin mendapat giliran untuk memberikan khutbah. Begitu naik mimbar ia bertanya kepada para jamaah: “Wahai jamaah sekalian, apakah kalian sudah tahu apa yang akan aku khutbahkan hari ini?”
Para jamaah menjawab: “Beluum.”
Sang Mullah menjawab: “Kalau begitu, apa gunanya aku berkhutbah kepada orang yang tidak tahu apa yang akan aku khutbahkan.” Lalu sang Mullah pun turun mimbar dan pulang.
Minggu selanjutnya, kembali Mullah mendapat jadwal khutbah. Pertanyaan yang sama kembali ia ajukan kepada jamaah. Kali ini para jamaah yang masih ingat reaksi Sang Mullah minggu sebelumnya, serempak menjawab: “Sudaah.”
Mullah Nasruddin menanggapi: “Kalau begitu apa gunanya aku berkhutbah kalau kalian sudah tahu isinya?” Mullah pun kembali turun mimbar dan pulang.
Hal yang sama terjadi di minggu selanjutnya. Kali ini para jamaah mengatur strategi untuk menjawab pertanyaan Mullah. Sebagian menjawab “sudah” dan sebagian menjawab “belum”.
Sang Mullah pun sambil tersenyum merespon: “Kalau begitu, yang sudah tahu silahkan memberi tahu yang belum tahu.” Dan beliau pun lagi-lagi turun dari mimbar.
Sekali-sekali aku ingin mengikuti gaya Sang Mullah favorit ini, menghindar dari kewajiban dengan retorika yang unik dan bermakna.
Aku bayangkan besok-besok setiap kali orang bertanya apapun kepadaku atau memintaku berbicara atau menulis sesuatu, cukup aku jawab saja: “Monggo, cek di Google saja, semuanya ada, Insyaallah barakah.”
hampir tiap hari orang-orang baik di sekelilingku banyak sekali yang memintaku untuk menulis atau mengirimkan tulisan ke media yang mereka miliki.
Tentu saja permintaan itu lahir dari kebaikan hati mereka dan prasangka baik mereka bahwa aku ini bisa menulis.
Padahal jujur saja, setiap kali permintaan menulis itu datang, muncul masalah: Aku bingung mau menulis apa?
Semua yang ingin kuomongkan sudah sangat banyak orang yang menuliskannya, bahkan dengan kualitas yang jauh lebih baik dibanding apa yang mau kutuliskan.
Di puncak perkembangan teknologi informasi hari ini, dengan sangat mudah orang dapat memuaskan rasa ingin tahu, memenuhi kebutuhan akan informasi dan menjalankan kewajiban memperdalam pengetahuan, hanya dengan sekali menjentikkan jemari.
Mulai dari gagasan tokoh-tokoh besar hingga celotehan anak-anak nongkrong di sudut jalan, semuanya dapat diakses dengan begitu mudahnya hari ini.
Kecanggihan teknologi informasi hari ini membuat hampir semua orang melek informasi, tentang apapun, bahkan hingga level obesitas informasi, kegemukan informasi, sebagaimana istilah Jean Baudrillard, sang filosof kritis dari Perancis.